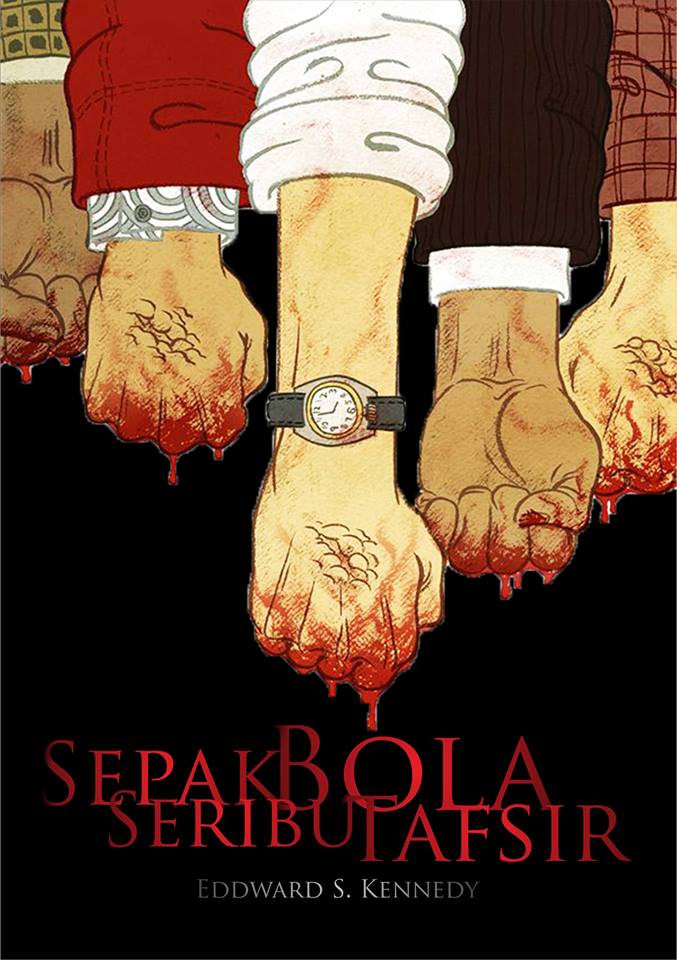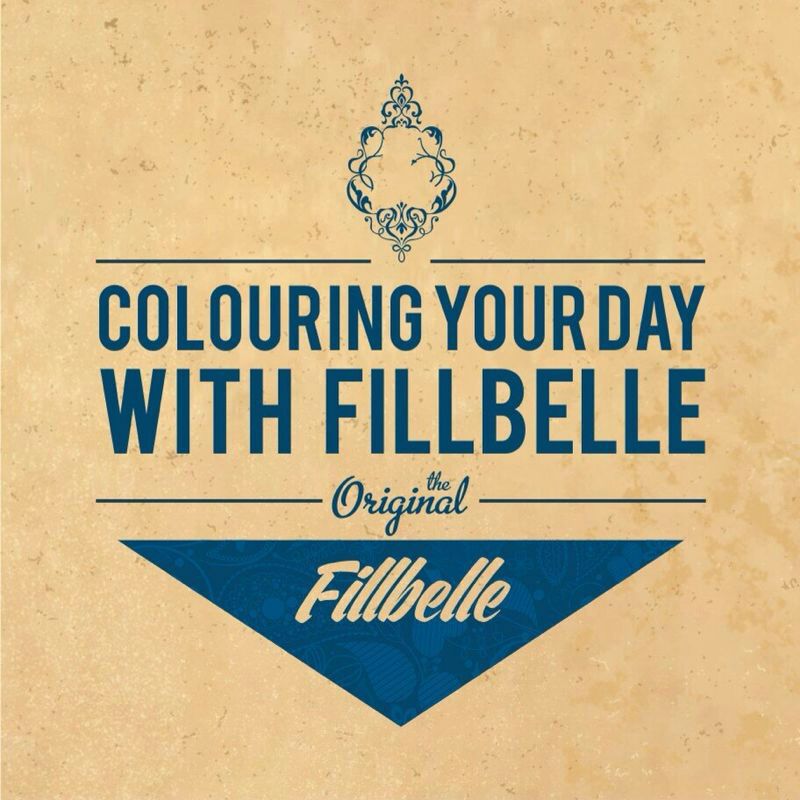Jogjapedia
Jejak Langkah ‘Ayam Kampus’ di Nusantara: Mulai Dari ‘Gundik’, ‘Nyai’, Hingga ‘Selir’
Satu ketika, Aan (bukan nama sebenarnya), salah seorang mahasiswa di universitas terkemuka di Jogjakarta, diajak oleh teman kosnya ke sebuah kafe. Di kafe tersebut ternyata sudah menunggu dua orang perempuan cantik. Saat berkenalan, kedua perempuan itu mengaku bernama Reni dan Sinta (bukan nama sebenarnya) dan juga tengah kuliah di Jogja.
Aan yang kebetulan tengah jomblo saat itu senang-senang saja mendapat kenalan perempuan cantik, apalagi mereka semua ramah dan mudah bergaul. Keakraban tersebut membuat Aan memberanikan diri untuk mengajak kedua perempuan tadi ke diskotik. Gayung pun bersambut, kedua perempuan itu mengiyakan ajakan Aan. Berangkatlah kedua pasangan tersebut menuju salah satu diskotik ternama di Jogjakarta.
Tentu saja tak afdol rasanya jika di dalam diskotik tak menenggak minuman keras. Aan menyadari betul hal ini. Untuk itu, ia pun lalu memesan bergelas-gelas minuman keras untuk temannya dan kedua perempuan tadi. Setelah dirasa letih karena kepala mulai berat, terlebih malam juga semakin larut, kedua pasangan itu lantas memutuskan untuk pulang.
Di perjalanan, kedua perempuan tersebut mengatakan kosnya sudah dikunci, sementara mereka pun tak memiliki kunci cadangan. Seolah menyadari perkataan tersebut adalah “kode”, Aan dan temannya lalu membawa mereka ke kos untuk menginap. Kedua perempuan itu pun tak menolak. Cerita selanjutnya sudah bisa ditebak, mereka lalu melakukan hubungan intim.
Menjelang matahari terbit, Reni—yang bersama Aan—meminta untuk diantarkan pulang. Aan pun langsung bergegas untuk mengantarkannya. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Aan setelah Reni menyebut bahwa Aan harus membayar satu juta rupiah karena telah menggunakan “jasanya” selama satu malam. Aan yang merasa dijebak pun menolak membayar uang tersebut, tetapi, seolah sudah tahu jika Aan akan menolak, ia lalu mengancam akan melaporkan hal ini kepada preman-preman yang dikenalnya.
Untuk membuktikannya, ia pun langsung menelpon salah seorang preman saat itu juga. Aan mulanya tidak percaya, tetapi setelah Aan membesarkan pengeras suara di handphone-nya, Aan baru sadar bahwa Reni tidak main-main dengan ancamannya. Walhasil, Aan pun menyerah, ia lantas mengambil uang di atm sembari mencarikan Reni taksi. Ia berkenan membayar, tetapi menolak mengantar Reni pulang.
Cerita di atas sejatinya merupakan kisah fiktif yang disadur dari berbagai pengalaman orang banyak mengenai fenomena “ayam kampus”. Sebenarnya seperti apa sejarah “ayam kampus” atau, menyitir istilah Tempo, “gundik terdidik”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘gundik’ diartikan (1) istri tidak resmi; selir; (2) perempuan piaraan (bini gelap). Kata ‘gundik’ sendiri pada zaman kolonial Hindia Belanda memiliki pengertian yang nyaris sejajar dengan kata ‘nyai’ yang dapat diartikan sebagai selir, atau wanita piaraan para pejabat dan serdadu Belanda. Pun demikian, adapun faktor pembedanya adalah garis nasib.
Begini. Pada masa awal kolonisasi Hindia Belanda, para pejabat Belanda datang tanpa disertai mevrouw (nyonya). Tentu saja hal ini meresahkan secara seksual bagi para kumpeni tersebut. Difaktori kepentingan tersebutlah, juga status sosial para pejabat tersebut, mereka mulai memburu mevrouw lokal, yang mana pilihan jatuh kepada para ‘nyai’. Pertanyaannya, mengapa ‘nyai’ yang dipilih, dan bukan perempuan lain?
Seorang ‘nyai’ berada dalam posisi yang tinggi secara ekonomis, tapi rendah secara moral. Secara ekonomis, mereka berada di atas rata-rata perempuan pribumi yang bukan bangsawan. Para ‘nyai’ mengenakan kain songket bersulam benang emas dan perak, mengenakan tusuk konde roos, peniti intan, dan giwang yang terbuat dari berlian. Cara berjalan mereka pun menyiratkan aura permaisuri otodidak.
Akan tetapi, harus digarisbawahi, lambat laun pengertian kata ‘nyai’ lambat laun memiliki pergeseran makna seiring dengan perkembangan era politik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah karya sastra Indonesia
Cerita Nyai Dasima yang dikarang G. Francis, misalnya. Di sana digambarkan betapa Dasima, perempuan dari Kampung Koeripan menjadi nyai Tuan Edward W, adalah sosok perempuan yang serong, bodoh, culas, kemaruk harta, dan rendah secara moral. Setelah terus-terusan dimanja oleh Edward, Dasima justru serong dengan Baba Samioen dari Kampung Pedjambon. Penggambaran tokoh ‘nyai’ yang nyaris serupa juga dapat dilihat dalam cerita Si Tjonat karangan F.D.J. Pangemanann.
Pengertian ‘nyai’ yang berbeda kemudian (di)muncul(kan) oleh Pramoedya Ananta Toer dalam salah satu roman tetraloginya, Bumi Manusia. Di sana Pram menciptakan tokoh Nyai Ontosoroh: seorang ‘nyai’ yang tak lagi hidup sebagai objek seksual para kompeni, sebagai pelengkap prestise sosial. Lebih jauh, Nyai Ontosoroh pun bukan perempuan amoral tukang serong dan berwatak mata duitan.
Nyai Ontosoroh, oleh Pram, digambarkan sebagai sosok perempuan tangguh, independen, dan menolak bergantung kepada sosok laki-laki. Ontosoroh, jika boleh dikatakan, adalah padu padan yang sempurna dari paras perempuanTimur yang elok dengan keuletan, keberanian, dengan kecerdasan sekaligus sikap mandiri khas seorang perempuan Eropa. Dengan pemerian karakter seperti itulah, Pram dapat dikatakan telah berhasil menggiring pengertian kata ‘nyai’ pada khususnya, dan sosok perempuan pribumi pada umumnya, untuk ikut ambil bagian dari politik narasi kebangsaan Indonesia sepanjang awal sampai pertengahan abad ke-19, masa awal kebangkitan nasional.
Adapun alasan utama mengapa muncul praktik pergundikan di Nusantara, selain kebutuhan faktor seksual dan prestise sosial para tuan Belanda, adalah aturan dari Gubernur Jenderal Belanda, JP. Coen, yang mewajibkan bagi setiap pria Belanda yang menikah dengan perempuan pribumi dilarang membawa keluarganya kembali ke Belanda. Peraturan ini tentu saja membuat para kompeni lebih merdeka untuk bermain cinta dengan para perempuan pribumi. Lantaran hal inilah yang melahirkan istilah ‘gendak’ untuk menyebut para ‘nyai’ yang ditinggalkan begitu saja oleh para londho.
Tak hanya dalam lingkar kompeni, praktek pergundikan sejatinya juga lazim dalam kehidupan kaum aristoktat, raja, dan bangsawan, jauh sebelum kolonialisme Belanda tiba di Nusantara. Perempuan-perempuan yang bukan merupakan istri utama (permaisuri) disebut sebagai ‘selir’.
Di kalangan aristokrat Jawa, kebutuhan akan ‘selir’ bahkan menjadi menu wajib.‘Kewajiban’ itulah yang membuat status sosial ‘selir’ tak dianggap “serendah” ‘gundik’ atau ‘nyai’. Dan karena ‘kewajiban’ itu pula, tak mudah bagi perempuan untuk mendapat label ‘selir’ dalam lingkaran kultural kerajaan di Jawa. Mengapa demikian?
Alasannya sederhana: menjadi ‘selir’ berarti kemampuan ekonomi akan naik dengan drastis. Dengan menjadi ‘selir’, seorang perempuan akan masuk ke dalam level kehidupan priyayi. Dan bagi ‘selir’ yang mampu membuat Raja menurut, maka ia jelas akan mendapat penghasilan bulanan yang tinggi. Itulah mengapa sejak kecil seorang perempuan di Jawa dibekali dengan kemampuan membatik, menari, sopan santun dan pemahaman tentang adat keraton. Begitu mulai beranjak dewasa diperkenalkan dengan kehidupan keraton dengan menjadi penari dan lain sebagainya. Dari situlah muncul kemungkinan sang perempuan ini terpilih menjadi selir.
Bagi para Raja sendiri, banyaknya selir menjadi penanda semakin kuatnya dia dalam ranah politik. Akan tetapi, biasanya para Raja tak menempatkan para ‘selir’ mereka dalam istana, melainkan pada sebuah tempat khusus. Di Jogjakarta, Pasar Kembang atau biasa dikenal dengan istilah Sarkem, konon disebut sebagai tempat penyimpanan para selir dan gundik Raja serta Bangsawan Jawa.
Jadi, bagi siapa saja yang berkenan berkunjung ke Sarkem, saya sarankan Anda untuk menganggap diri Anda sebagai seorang Raja. Jika perlu, berpakaianlah selayaknya bangsawan saat berkeliling di kompleks tersebut. Niscaya, saya yakin 100%, Anda pasti, pasti akan dikira orang gila.
Bukan hal yang aneh jikalau kemudian Anda merasa menemukan ada sebuah persamaan antara ‘gundik’, ‘nyai’, atau ‘selir’ dengan fenomena ‘ayam kampus’ setelah membaca sedikit pemaparan di atas. Apa persamaannya? Tentu saja tingkat eksklusifitas. ‘Ayam kampus’ atau ‘gundik terdidik’, nyaris tidak mau jika disamakan dengan pekerja seks komersil yang biasa ditemui di keremangan warung tenda, gubuk-gubuk pinggir rel kereta, atau di trotoar jalan.
Selain itu, sistem kerjanya pun berbeda. Jika para PSK menerima segala jenis laki-laki dengan bentuk wajah dan bau keringat yang beraneka rupa, maka ‘ayam kampus’ cenderung memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Tak jarang ‘ayam kampus’ menolak mereka yang berduit lantaran wajah atau kualitas fisiknya tak sesuai selera. Dan juga, pemesanan ‘ayam kampus’ juga tak semudah jasa pelayanan PSK. Ada semacam level sebelum memasuki acara puncak bersama ‘ayam kampus’, seperti berbelanja, makan enak, ke tempat hiburan, dan sebagainya.
Berdasarkan data survey yang pernah dihimpun Retorika, majalah Internal Senat Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga di tahun 1993—yang juga terbit dalam majalah Tempo di tahun yang sama—, 0,02 persen mahasiswi dari perguruan-perguruan tinggi ternama di Surabaya adalah PEREK atau akronim dari ‘Perempuan Eksperimen’, istilah yang pada hari ini dikenal dengan sebutan ‘ayam kampus’. Ketika kemunculan data tersebut, kegegeran pun muncul di seantero kampus, bahkan di Surabaya sendiri. Sumiyanto, nama penulis laporan survey tersebut, bahkan harus dihajar ramai-ramai oleh 15 mahasiswa Fisip karena dianggap telah membongkar aib kampus.
20 tahun pasca kejadian tersebut, kini fenomena ‘ayam kampus’ telah berkembang di mana-mana. Tentu dengan level ekslusifitas yang berbeda-beda. Ada yang bertarif sampai puluhan juta sekali kencan, ada yang ratusan ribu, atau ada yang cukup dengan membelanjakannya berbagai barang di mal, yang mana jika dikalkulasikan nominalnya tak jauh berbeda dari kisaran ratusan atau puluhan juta rupiah.
Dengan demikian, maka tak usah diherankan jika pelanggan setia ‘ayam kampus’ adalah para pejabat, politisi, atau pengusaha-pengusaha muda yang telah mapan secara finansial. Bukan seperti cerita Aan di atas, mahasiswa dengan kemampuan ekonomi seadanya yang, setelah menggunakan jasa ‘ayam kampus’dengan tarif sebesar satu juta rupiah, harus makan nasi aking sebulan penuh.