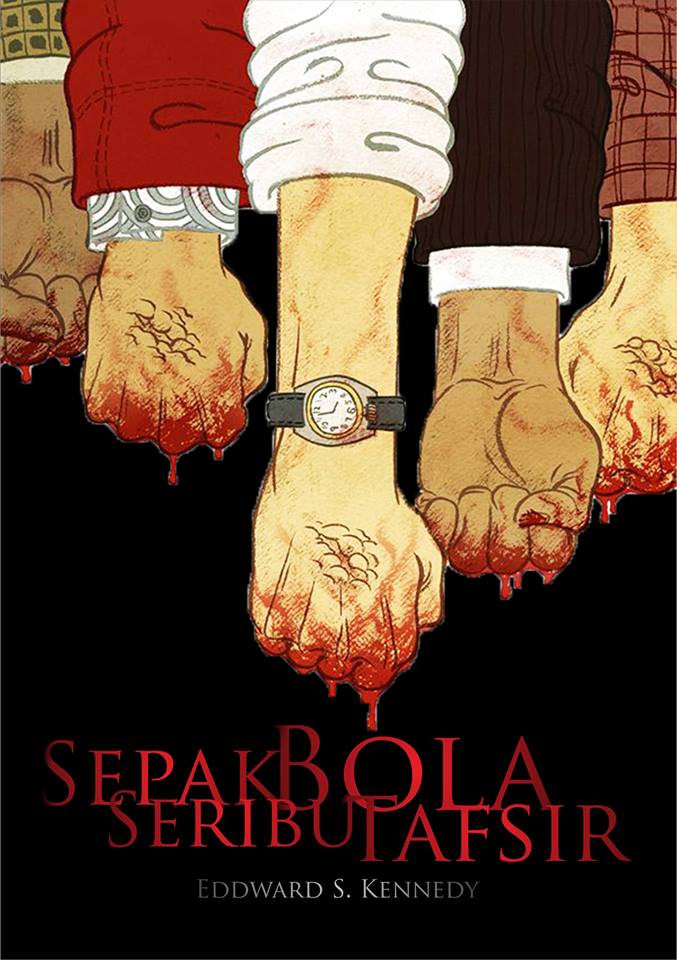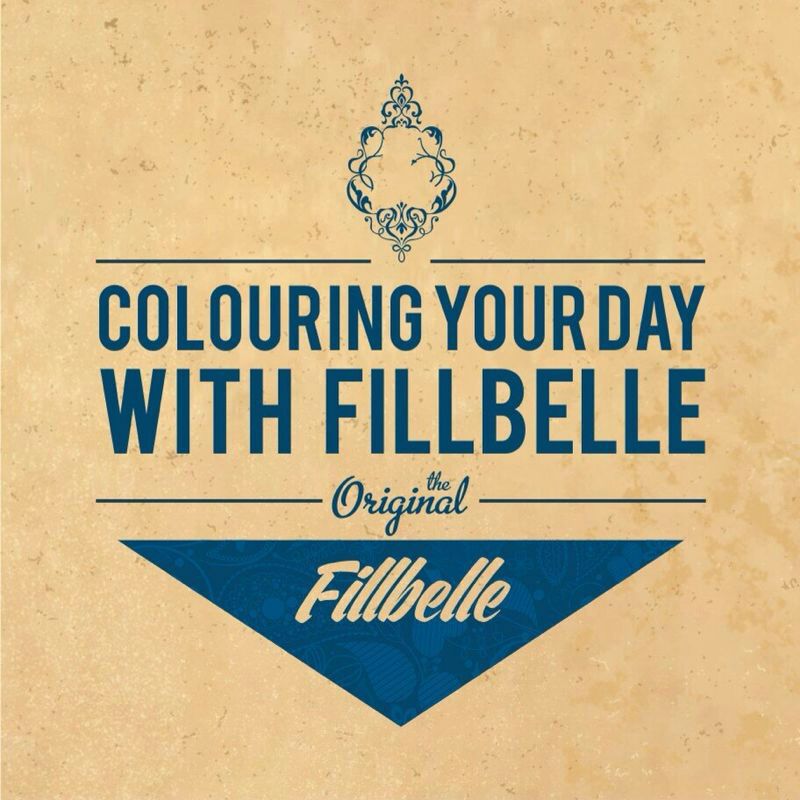Mengapa (Dipaksa) Menikah Itu Menyebalkan?
Sebenarnya tak ada yang salah dengan Romli. Di usianya yang masih 26 tahun, ia telah mengantongi gelar sarjana dan kini tengah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Nominal gajinya pun dirasa lebih dari cukup bagi seorang pria yang masih melajang. Dengan demikian, Romli masih bisa menabung sambil sesekali berfoya-foya.
Akan tetapi, apa yang Romli rasakan justru tak seenak yang dibayangkan. Fakta bahwa dirinya masih bisa bebas melakukan apa saja tak dapat menyembunyikan apa yang membuatnya gelisah: tenggat untuk menikah. Romli memang belum menentukan kapan ia akan membina keluarga. Bahkan ia juga belum punya pacar. Selama ini juga tak pernah memusingkannya, sampai kemudian, dalam beberapa bulan belakangan ini, keluarganya “meneror” dengan pertanyaan “kapan menikah?”.
Sebagai anak tertua, Romli memang punya “kewajiban” untuk menikah terlebih dahulu. Itulah norma sosial yang berlaku pada mayoritas masyarakat di negeri ini. Apalagi adik perempuan Romli seorang perempuan yang usianya tak terlampau jauh dengannya dan juga telah memiliki calon suami. Romli kian gelisah setelah ibundanya merengek nyaris setiap hari karena ingin segera memiliki cucu. Sementara sang ayah kerap melontarkan kalimat mengiris yang secara implisit bermakna sama dengan ibunda: “usia ayah kan sudah tidak muda lagi, siapa tahu besok ayah sudah meninggal…”
Alhasil, Romli kian gelisah. Ia mencoba mengikuti kemauan keluarga—dan masyarakat—untuk segera menikah. Langkah pertama yang ia mulai adalah dengan mencari pacar. Akan tetapi, tentu hal itu tak semudah seperti membalikan telapak tangan. Kendati secara materi mapan, dan secara fisik ia juga “menjual”, Romli kerap kesulitan menyesuaikan diri dengan sifat perempuan yang diincarnya selama ini. Sikapnya yang cenderung idealis membuat Romli agak keras kepala untuk bernegosiasi dengan pribadi orang lain. Terlebih, yang Romli cari adalah calon istri, bukan pacar biasa.
Berbulan-bulan Romli mencari perempuan yang benar-benar cocok dengannya. Mulai dari aktif jejaring sosial sampai mengikuti berbagai komunitas, Romli lakukan agar ia bisa segera mendapatkan calon istri. Tetapi hasilnya masih nihil. Sementara itu, keluarga terus “meneror”-nya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Romli kian pusing setelah ia mendapatkan banyak undangan menikah dari teman-temannya. Antara pusing dan iri, Romli kini tak tahu pasti.
Suatu ketika, Romli berkenalan dengan Leila di sebuah supermarket. Ketika itu secara tak sengaja Romli menabrak Leila yang tengah membawa banyak barang perbelanjaannya. Romli pun lantas meminta maaf sambil lekas memunguti barang-barang Leila yang jatuh berserakan di lantai. Leila pun terkesan dengan sikap Romli tersebut, sementara Romli sendiri seolah sadar bahwa perempuan yang ditabraknya saat itu tengah mengirimkan “kode” melalui senyum manisnya. Singkat kata, mereka berkenalan.
Tak sampai dua minggu, Romli sudah berhasil merayu Leila untuk berkencan. Tempat pertama yang mereka kunjungi standar saja: bioskop. Setelah dari sana, mereka melanjutkannya dengan makan malam di sebuah resto yang tak jauh dari apartemen Leila. Sekitar pukul 23:00 WIB, Romli pun lantas mengantar Leila pulang. Lelila kembali kesengsem. Ia menangkap ada sikap seorang gentleman dalam diri Romli. Sementara Romli? Ia masih menahan diri, kendati jantungnya mulai sering deg-degan tiap melihat Leila tersenyum.
Hari demi hari, minggu demi minggu, telah dilewati Romli dan Leila bersama-sama. Pun demikian, keduanya masih enggan menyatakan cinta. Romli masih merasa nyaman dengan hubungannya bersama Leila saat ini di mana tak ada komitmen. Ada semacam ketakutan dalam diri Romli jika terburu-buru mengutarakan niatnya menjadikan Leila seorang istri. Untuk sementara, ia berhasil melenyapkan kegelisahan dirinya dari “teror” keluarga. Setidaknya, dalam hati Romli berkata, ia sudah punya teman dekat perempuan.
Sementara itu Leila sendiri setali tiga uang. Ia tak pernah mempermasalahkan sikap Romli yang selalu menjaga jarak untuk serius berhubungan. Ia merasa nyaman-nyaman saja selama ini. Justru dengan hubungan tanpa komitmen seperti ini Leila dapat menekan sikap protektifnya yang selama ini muncul ketika berpacaran. Ia tak perlu repot-repot mengirim pesan singkat setiap waktu, tak perlu curiga mengapa Romli telat menjemput atau absen menelponnya, juga tak perlu muluk-muluk membicarakan rencana-rencana indah di masa depan.
Posisi Leila dalam keluarga sejatinya tak jauh berbeda dengan Romli. Jika Romli adalah anak sulung yang sudah “ditodong” keluarganya untuk cepat-cepat menikah, sementara Leila adalah anak bungsu yang juga mulai sering diwanti-wanti oleh kedua orang tuanya untuk segera menuju pelaminan. Alasan orang tua Leila pun serupa dengan orang tua Romli: usia mereka tak lagi muda.
Leila pun memikirkan perkataan orang tuanya itu nyaris setiap hari. Terlebih, para sanak saudara juga telah mulai ikut membicarakan posisi Leila yang tak kunjung menikah. Hal-hal semacam itu membuat Leila merasa jengah dan gelisah sekaligus. Namun apa daya, jodoh yang dikejar tak pernah kesampaian. Sudah setahun lebih Leila hidup sendiri tanpa pacar, lebih-lebih (mantan) calon suami. Tetapi Leila sejatinya tak memiliki masalah dengan kesendiriannya itu. Sama sekali.
Ketika Leila menceritakan posisinya tersebut kepada Romli dalam sebuah acara makan malam, keduanya justru tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa aneh mengapa nasibnya segendang-sepenarian karena sama-sama “diteror” keluarga. Leila pribadi tak bermaksud menceritakan hal tersebut kepada Romli sebagai “kode” lain agar Romli segera meminangnya atau minimal membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Sama sekali tidak. Ia hanya merasa telah menemukan orang yang tepat untuk dibagi permasalahan.
Romli pun menganggapnya demikian. Setelah Leila menceritakan hal pribadinya tersebut, Romli justru mengutarakan niatnya untuk hidup selibat. Ia juga bercerita tentang ketakutannya untuk menikah: takut bosan dengan pasangan yang sama selama bertahun-tahun, takut memiliki anak yang keras kepalanya menyamai dirinya, takut rumah tangganya pecah, dan semacamnya. Leila berusaha mengerti, ia lalu menggenggam tangan teman dekatnya itu dengan erat.
Nyaris dua tahun lamanya Romli dan Leila menjadi sepasang teman dekat tanpa komitmen. Nyaris tak pernah ada masalah besar yang menyangkut urusan hati. Jika pun ada masalah, semua hanyalah riak kecil. Selama tiga tahun itu pula, keduanya terus menepikan “teror” keluarga masing-masing untuk menikah. Sampai suatu ketika, Leila harus pergi ke Jepang karena mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2.
Mengetahui kabar itu, Romli berusaha bersikap sewajarnya. Ia mengaku sedih karena harus kehilangan Leila, sementara Leila sendiri juga merasa belum mampu berpisah dengan Romli secara mendadak seperti ini. Akan tetapi, keduanya saling mengingatkan bahwa hubungan yang mereka jalin adalah tanpa komitmen. Rasa sayang yang mereka ciptakan adalah rasa sayang yang bukan memiliki. Dengan kesedihan yang wajar, keduanya bersepakat merayakan keterpisahan mereka juga dengan cara yang biasa-biasa saja: makan malam di resto favorit.
Kini, usia Romli sudah 30 tahun dan ia masih melajang. Pasca kepergian Leila ke Jepang, ia belum juga mencari penggantinya. Ia bahkan sudah kebal dengan berbagai “teror” keluarganya yang belum juga berhenti. Hari-hari Romli pun dijalani seperti biasa, kendati jabatan di kantornya telah cukup tinggi hingga membuat Romli mampu mengkredit sebuah rumah dan melunasi cicilan mobil.
Sesekali ia dan Leila saling menghubungi via video call, handphone, atau jejaring soial. Kali ini obrolan mereka berubah, mereka justru “meneror”—tentu dengan humor—satu sama lain dengan pertanyaan: “Udah punya calon belum?” Kapan nikah?”, dan sejenisnya. Keduanya hanya tertawa. Leila berkesempatan kerja di salah satu perusahaan di Jepang. Seperti Romli, ia pun belum memiliki calon suami dan tak tahu kapan akan mendapatkannya.
Di salah satu perbincangan mereka melalui video call, Romli sempat bertanya kepada Leila:
“Kalau nanti kamu jadi seorang ibu, sikap apa yang ga akan pernah kamu tunjukkan ke anakmu?” tanya Romli.
“Apa, ya? Banyak sih. Tapi yang jelas aku ga akan memaksa anak ku untuk menikah. Itu menyebalkan sekali, hahahaha…” jawab Leila.
Keduanya kembali tertawa riang, seperti biasanya.