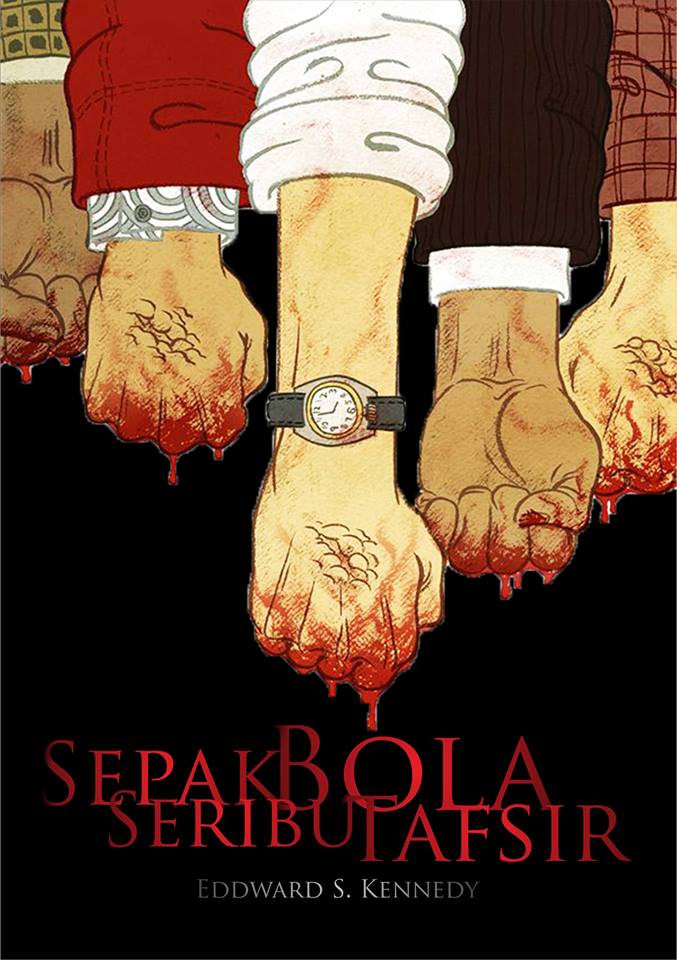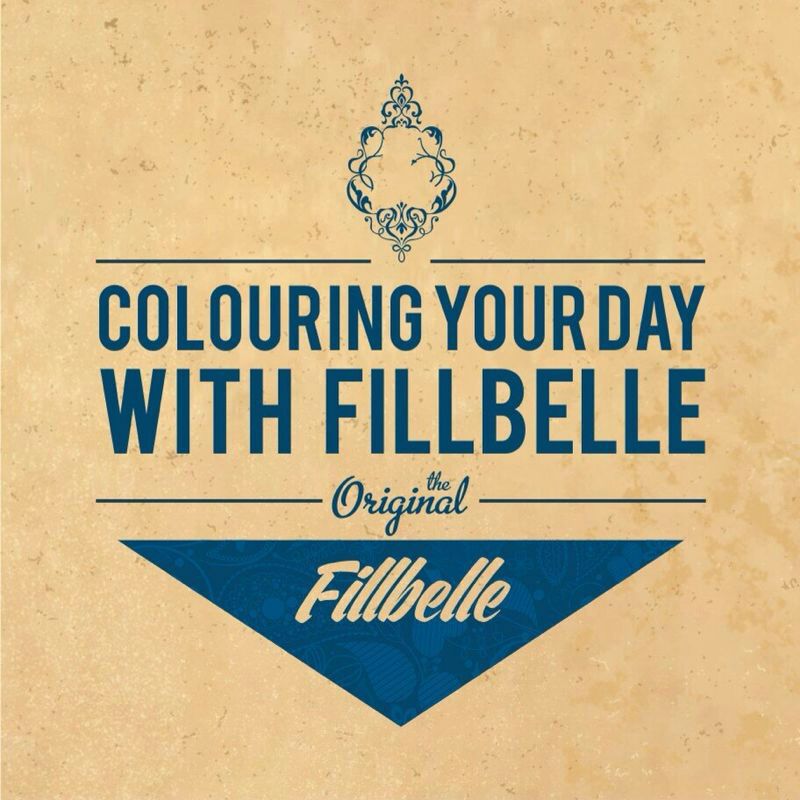Interaksi
Fetisisme Visual: Fotografi antara Barat dan Timur
Fotografi adalah sebuah relasi antara subjek dan objek. Antara pemotret dan terpotret. Tak pernah ada foto yang bisa berbicara, seperti apapun bentuknya, karena ia hanya benda mati, hanya selembar kertas dengan warna dan bentuk. Tapi foto selalu bisa untuk dibicarakan, dengan cara apapun.
Agus Sachari dalam Budaya Visual Indonesia (2007) mengatakan bahwa dalam sejarah kebudayaan Indonesia, peran budaya visual sebagai bagian dari percaturan pembentuk peradaban belum banyak ditelaah. Dalam konteks fotografi, pernyataan tersebut tentunya semakin menguatkan anggapan bahwa rezim fotografi lebih suka memapankan diri pada area penciptaan karya tinimbang “bermain” dalam telaah wacana kritis yang melingkupinya. Melubernya citra visual pelan-pelan menimbun lembaran kritik foto yang tak seberapa jumlahnya. Fotografi menjadi alat konstruksi yang kuat, baik dalam wilayah sosial, politik, gender, ras, kelas maupun gaya hidup. Dan ketika gaya hidup menguasai jaring-jaring hasrat visual dalam ruang kapital ekonomi, maka ia (fotografi) memerlukan korban untuk di-liyankan.
Sebagai bagian dari media visual yang populer, fotografi melahirkan spectator (penonton-pemandang foto) bagi dirinya sendiri (fotografi). Kehadiran spectator inilah yang kemudian merangsang serta menghidupkan mesin-mesin aparatus visual (fotografer beserta institusinya) untuk terus bergerak. Spectator menjadi semacam produk atas keberadaan fotografi, ia menjadi indikator tinggi/rendahnya kemenarikan penilaian terhadap foto yang dihadirkan. Tanpa adanya spectator, maka foto hanya lembaran benda bisu. Ia hanya angin lalu yang tak dibicarakan. Kehadiran spectator yang saya utarakan di atas menciptakan suasana dimana para aparatus foto “dituntut” untuk terus menggerakan roda visual, melalui perburuan (hunting), menghadirkan galeri foto baik melalui media massa maupun ruang galeri, baik virtual maupun non virtual.
Hunting menuju “timur jauh”, timur dengan segala keeksotisannya, keluguannya, serta ke”primitifannya” yang jauh dari hingar bingar kota besar. Dari sinilah, dominasi antara subjek dan objek, antara fotografer sebagai subjek yang menodongkan lensa dengan objek foto yang tersenyum di depan todongan lensa kamera.
Lumrah kita jumpai bagaimana pegiat komunitas foto, fotografer, ataupun pelancong menyiapkan dirinya untuk memotret di wilayah pedalaman. Menyaksikan upacara ataupun festival adat. Pertanyaan sederhana, klise namun cukup pelik: ketika hasil foto tersebut menghiasi sampul majalah ataupun masuk galeri dan menjadi perbincangan luas, lalu apa yang mereka (objek foto) dapatkan?, dalam konteks ini tentu saja bukan mereka yang berkecimpung dalam ranah foto model professional yang tentu saja akan mendapatkan bayaran secara materi. Tapi hal ini diperuntukan bagi mereka para “model” yang ke-etnisitasannya- mengandung daya komoditi. Terkadang, justru mereka malah mendapatkan jumlah pengunjung yang semakin bertambah, bukan? Pengunjung yang akan kembali berlomba menodongkan lensa ke diri mereka.
Keterpesonaan, mungkin itulah yang senyatanya merangsang hasrat visual fotografer dalam melihat etnis yang memiliki daya pesona dalam tatapan lensa. Menanamkan anggapan jikalau mereka memiliki nilai lebih yang bisa dikomoditaskan karena faktor estetis, unik dan menarik. Mereka memotretnya dan menjadikannya sebagai komoditi yang memiliki nilai pesona tertentu. Yasraf mengistilahkan hal yang demikian dengan Fetisisme komoditi. Katakanlah mereka yang berada di timur jauh, Papua. Seperti yang rutin kita dengar beritanya perihal festival Lembah Baliem yang menarik perhatian para pelancong dan fotografer untuk berburu foto di sana. Ataupun dalam perayaan-perayaan adat lainnya. Daya pikat kesukuan, menjadi pijakan untuk membingkai mereka lalu mengkomoditikan sebagai objek foto.
Kekaguman dan kegumunan inilah yang kemudian menjadikan mereka liyan yang bernilai lebih dan memiliki nilai jual. Nicholas Mirzoeff dalam An Introduction to Visual Culture (1999) mengatakan bahwa dalam relasi pandang fetis, realitas eksis tetapi hasrat dari si pemandang melapisi penglihatan. Pada titik inilah spectator menerima fotografi sebagai suatu “kegumunan” dan karena faktor tersebut membuat ia begitu menilai lebihkan sebuah realitas foto tersebut.
Kegumunan yang mematri dalam penglihatan inilah yang kemudian menanamkan bahwa mereka adalah objek yang menarik, eksotis penuh pesona. Fotografi seperti tengah mendominasi dan tetap berusaha “memelihara stereotip” dalam diri sang objek. Dominasi dan sub-ordinasi antara fotografer dan objek terbangun melalui perangkat kamera. Dengan melakukan pengobjekan terhadap pihak lain, artinya mereka tengah membangun jejaring relasional yang tak setara.
Sepulang dari pelosok daerah, mereka mengolah lalu memamerkan, memuat dalam media, atau bahkan terkadang mengikutsertakan dalam perlombaan fotografi, tentu saja dengan harapan keuntungan ekonomi. Fotografi dan perburuan objek ke penjuru daerah mengingatkan pada suatu masa ketika para eropa datang ke Indonesia berpuluh-puluh tahun silam dengan membawa kamera. Sebagai agen visual, mereka telah membuka mata kekaguman barat akan indahnya Indonesia. Sebut saja Alferd R. Wallace, seorang yang kemudian kita kenal sebagai peletak garis imajiner flora dan fauna:garis Wallace. Ia mengagumi sebuah foto sungai dengan vegetasi tropis yang tumbuh di dinding sungainya, foto tersebut adalah jepretan Woodburry di akhir tahun 1800-an. Sebenarnya foto tersebut biasa saja, dan pemandangan seperti itu gampang sekali kita temui. Namun bagi mereka, lingkungan seperti itu adalah hal yang langka, vegetasi yang hampir tidak akan ditemui di sana (barat). Kegumunan bernilai lebih dari selembar foto memang senyatanya akan mengundang spectator berbicara lebih banyak.
Sekarang fotografi seperti sedang membangun jiwa-jiwa kolonial atas bangsanya sendiri, tidaklah berlebihan jika kita menyaksikan bagaimana para peminat fotografi terbang menuju wilayah jauh, mencari keuntungan atas wilayah yang mereka kunjungi, motif keuntungan ekonomi visual. Merujuk dari fenomena subaltern yang ditunjukan oleh Spivak bahwa dalam kolonialisme tidak hanya terjadi penaklukan fisik, namun juga penaklukan pikiran, jiwa, dan budaya. Menjadikan mereka sebagai objek foto yang secara “terpaksa berbuat” atas kesadaran kehadiran lensa membuat mereka berada pada posisi terjajah secara visual yang inferior dan bisu.
Apa hendak dikata, modernitas menuntut gaya hidup yang semakin mengada. Kontestasi kelas visual hanya bisa ditentukan melalui pengkaryaan yang menurut mereka adalah karya monumental dan layak dihargai oleh subjek lain. Bahwa dominasi yang demikian memang mengelola keberjarakan antara barat dan timur, antara pusat dan daerah. Menyitir dari apa yang pernah diungkapkan oleh Sontag bahwa fotografer layaknya burung nasar yang terbang ke segala penjuru untuk berburu momen.
Dengan meminjam terminologinya Said tentang orientalism, saya ingin mengatakan perihal relasi “barat” dan “timur” dalam fotografi. Bahwa orientalism adalah konstruksi historis terhadap masyarakat dan budaya timur, timur yang menurutnya asing, terliyankan dan sering disebut sebagai sesuatu yang menarik, eksotis, dan juga sering distereotipekan sebagai masyarakat yang kasar, amoral, kanibal, terbelakang, dan masih primitif.
Jiwa-jiwa kolonial tumbuh melalui perangkat kamera yang kemudian memosisikan diri sebagai barat yang serba lebih untuk melakukan dominiasi atas timur yang di-objekan. Lalu bagiamana timur memandang “barat” yang datang secara bergerombol dan serta merta mengacungkan lensa kamera ke arah mereka? Merasa senang atas kedatangan “barat” (baca:fotografer) yang menodongkan kamera, lalu mereka tersenyum dengan sadar kamera, tentu saja. Menyenangkan hati para fotografer, namun menyiratkan sisi-sisi inferioritas sang objek, bukan?
Perjalanan para fotografer ke timur dengan bekal referensi pemikiran yang sudah berdiam dalam batin mereka tentang timur, tentang suku pedalaman, tentang sudut pandang, tentang visual yang akan dihasilkan menjadi semacam “penguasaan sejak dalam pikiran”.
Bagaimana jika jalan ceritanya kita ubah, kita balik. Bagaimana jika mereka yang sering diobjekan karena nilai-nilai kesukuan dan etnisitas yang dianggap bernilai –“jual”- tinggi dalam tatapan visual melakukan “pembalasan”. Menjadikan subjek yang sering menodongkan lensa menjadi objek buruan mereka. Katakanlah mereka mengunjungi ibukota, lalu mereka bergerilya, menyelinap di antara gedung-gedung tinggi, memotret mereka yang tengah stress berdasi, memasuki café-café, melihat dan memotret pergaulan muda-mudi ibukota, dan sesekali berdiri di antara kamacetan ibukota, lalu memotret dengan mengarahkan lensa tepat dimuka mereka yang tengah stress dilanda macet. Lalu pulang dan menggelar pameran di balai desa ataupun di balai pertemuan warga dengan tajuk “eksotika ibu kota”. Bagaimana?
Daru Aji
Pemerhati Fotografi.