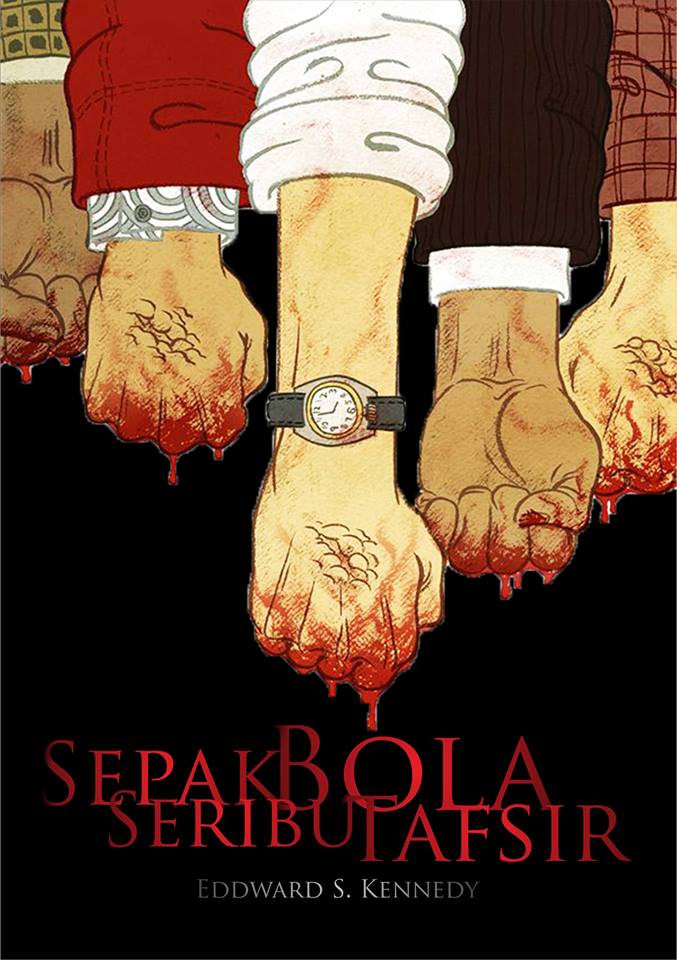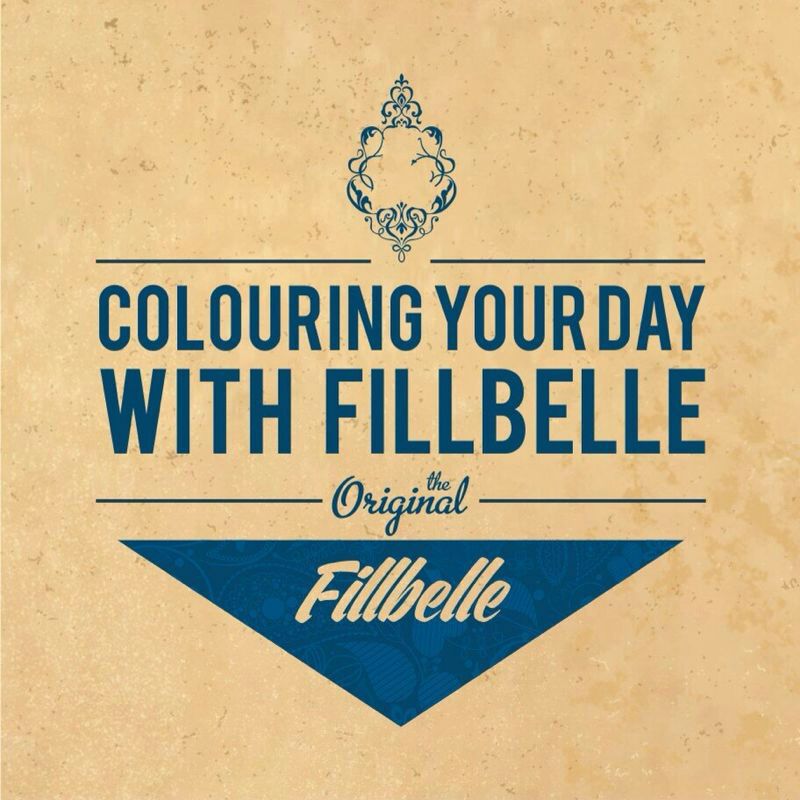Interaksi
Opini Pembaca: Fantasi Menggelikan dari Ritual Lima Tahunan
Jika ditanya momentum apa yang paling menggelikan dalam sebuah negara, saya akan dengan tegas menyebut: segala peristiwa yang terjadi menjelang pemilihan presiden!
* * *
Nyaris dua bulan ini Indonesia diseraki dengan berbagai adegan jilat-menjilat, gontok-menggontoki, antar sesama pendukung masing-masing calon presiden. Mereka sama-sama menyodorkan argumentasi untuk menjatuhkan, untuk mendiskreditkan. Demi memuluskan langkahnya, tak jarang mereka melakukan strategi manipulatif yang berujung fitnah. Dan yang terburuk dari semuanya adalah: kedegilan itu dilakukan secara vulgar dan penuh kesadaran.
Mari kita lihat:
Kubu Joko Widodo, misalnya, mati-matian menyerang rivalnya, Prabowo Subianto, dengan terus-menerus menggelontorkan masalah HAM yang memang menjadi persoalan utamanya. Merasa kurang, mereka para barisan tim sukses itu juga terus melontarkan agitprop kepada masyarakat tentang latar belakang militer Prabowo yang dinilai tak akan cocok dengan mayoritas rakyat sipil Indonesia. Semua terus dilakukan, tanpa jeda, massif, di segala tempat, di segala waktu.
Apa yang kemudian terjadi? Mendadak, persoalan HAM menjadi obrolan menarik bagi para anak-anak muda di Seven Eleven ketimbang koleksi vinyl atau video klip Raisa terbaru. Dengan tiba-tiba, ritual “Kamisan” yang digelar ibu-ibu luar biasa di depan istana negara yang entah kapan runtuhnya itu, menjadi perayaan segenap orang yang kulitnya terlalu mulus untuk terkena cahaya matahari dan debu jalanan jam 12 siang.
Tentu saja, kubu Prabowo tak tinggal diam. Dengan dimotori oleh Fadli Zon, sosok cerdas yang konon hafal di luar kepala Das Kapital berbahasa Rusia itu, tetapi entah mengapa merasa perlu untuk menjadi sastrawan handal, mereka aktif menyindir Jokowi sebagai pemimpin “opor kaki” yang tak mampu mengemban janji. Tanpa mengenal istirahat, timses Prabowo, yang juga dibantu oleh sejumlah juragan media, terus menerus mempersoalkan betapa culunnya Jokowi ketika berhadapan dengan Megawati.
Sementara itu, para partisan kedua kubu yang merasa lebih akademis, memilih berkampanye “terhormat” dengan data sebagai landasannya dan statistik sebagai peluru politiknya. Hitung-hitungannya njlimet, pilihan diksinya berbobot, tema perdebatannya pun jauh lebih canggih dan tentu saja berkelas. Mereka beradu argumen dengan saling menelanjangi visi-misi kedua capres kesayangan mereka, mulai dari ekonomi, politik, kebangsaan, terserah.
Lalu, apa yang kita dapat? Tak ada. Semua narsisisme kolektif ini, semua pemberhalaan sosok ini, hanyalah gegap gempita pengulangan dari kredo murahan itu: “Pilihlah yang terbaik di antara yang terburuk”.
Narsisisme tetaplah narsisisme tanpa atau dengan data. Pemberhalan akan selalu menjadi pemberhalaan, memakai atau menolak statistik. Semua hanya membutuhkan fundamentalisme yang (dipaksa) logis sebagai bahan bakarnya.
Inilah ritual lima tahunan yang menggelikan itu. Jika pun ada pembeda, kini dagelannya lebih variatif. Kelucuannya dirasa lebih cerdas. Dan, oh, mulai bermunculannya lembaga edukasi politik yang ditujukan bagi para anak muda yang ganteng dan cantik, yang gaul dan berpendidikan. Betapa indahnya.
Jika di masa pra-reformasi semua yang subversif adalah membagikan pamflet-pamflet propaganda sambil menyanyikan “Darah Juang” di aspal yang terik atau membaca fotokopian Bumi Manusia secara sembunyi-sembunyi, maka hari ini, Anda cukup mencari foto pejabat yang tak Anda sukai di Google, editlah foto tersebut dengan memasang kata-kata sekehendak hati atau, jika ingin lebih berbobot, buatlah tulisan sarkasme dan dipajang di midjournal.com. Sesederhana itu.
Muncul pertanyaan lagi: inikah demokrasi yang didengung-dengungkan itu? Inikah kebebasan berpendapat yang sering disuarakan Goenawan Mohamad dan sejawatnya itu? Jika benar, serendah inikah mutunya? Jika salah, mengapa kita mesti merayakannya? Apa yang diharapkan para intelektual menara gading itu dari “pendidikan” politik semacam ini?
Apakah mereka berpikir, masyarakat, ya, masyarakat miskin yang nasibnya klise dan tak lebih jadi objek para ekonom itu, akan mengangguk-angguk paham dan mendadak ikut cerdas karena dicekoki perseteruan banal semacam ini?
Sementara itu, mereka yang berdiri dalam barikade golongan putih hari ini tak ubahnya para hipster politik. Yang penting berbeda, yang penting menolak. Esensi? Nol belaka.
Jika Anda mengeluh karena tak mendapat apa-apa dari tulisan ini, ya memang begitu tujuannya. Anda yang mencari solusi silakan tonton Mario Teguh atau berkunjung ke Ki Joko Bodo. Sementara bagi Anda yang mencaci, saya sungguh berterima kasih, karena Andalah sejatinya pilar-pilar utama, ksatria berani mati penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab tanpa Anda semua, Indonesia nanti justru akan menjadi sebuah negeri yang indah dan permai, sebuah negeri di mana perbedaan betul-betul dihayati dan tak hanya menjadi jargon yang keluar dari Ruhut Sitompul dan Farhat Abbas. Dan itu artinya, kawanku, sama saja dengan meyakini bahwa ada presiden yang benar-benar bekerja untuk rakyat: hanyalah fantasi.
Joko Dylan
Musisi Jogja