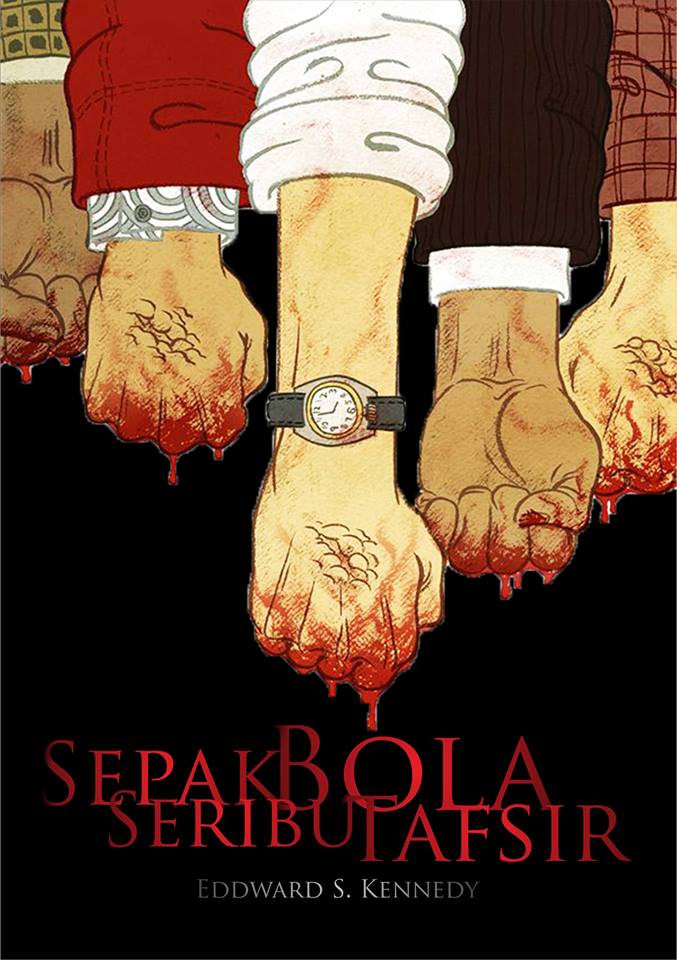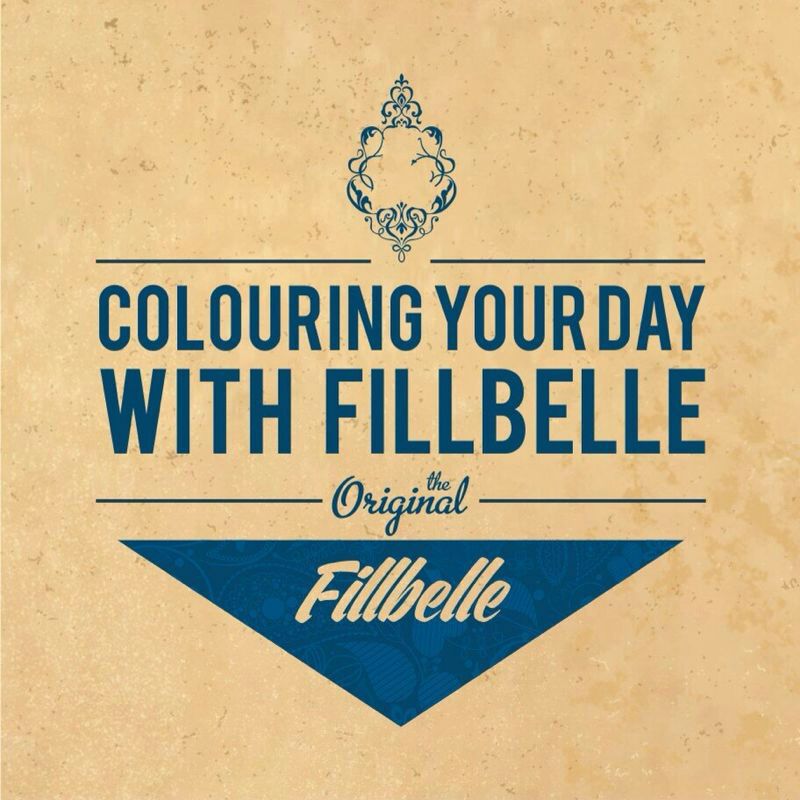Piala Dunia 2014
Mengapa Kita Tidak Usah Menonton Piala Dunia 2014?
Salah seorang novelis sekaligus esais asal Italia, Umberto Eco, pernah melontarkan pertanyaan (politik) paling masygul dalam sepak bola: “Apakah perjuangan bersenjata mungkin terjadi pada pertandingan Piala Dunia hari Minggu? Apakah mungkin terjadi revolusi pada pertandingan sepak bola hari Minggu?”
Melihat apa yang terjadi di Brasil dalam dua bulan belakangan ini, kita tahu jawaban untuk pertanyaan Eco adalah: Sangat mungkin!
Apa yang terjadi di Brasil hari ini adalah bentuk paling telanjang dari boyaknya wajah sepak bola yang dikapitalisasi sedemikian rupa oleh para pemburu rente. Lihatlah bagaimana media—yang nyaris tanpa jeda—mendesakan sepak bola ke dalam labirin kebutuhan primer masyarakat. Kita menjadi alpa, menjadi buta, menjadi berkata “ya” bahwa mengoleksi jersey Manchester United sambil menghina Liverpool seolah jauh lebih penting ketimbang tarif pendidikan yang kian melangit.
Sejatinya, sejak dulu, posisi sepak bola di Brasil sudah bertengger di puncak tertinggi sosial masyarakat bersama kebutuhan pokok lainnya. Jauh sebelum para cartolas itu datang dengan logika korporasi industri, orang-orang di Brasil sudah menjalani fase menikmati sekaligus menghayati sepak bola selayaknya hubungan senggama.
Lantaran sedemikian subtilnya pemahaman mereka terhadap sepak bola, maka tak usah heran jika Brasil—barangkali—menjadi satu-satunya negeri di dunia yang begitu banyak melahirkan jiwa-jiwa libertarian lapangan hijau. Anda tinggal pilih: Garrincha, Zico, Rivellino, Socrates, Didi, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, atau Neymar. Karena kecenderungan tersebut pula, maka tak perlu lagi dipertanyakan mengapa Brasil memiliki koleksi Piala Dunia terbanyak (lima kali).
Walau begitu, seintim apa pun hubungan masyarakat Brasil dengan sepak bola, semesra bagaimana pun relasi alam bawah sadar mereka dengan si kulit bundar, toh urusan kesejahteraan akan hidup tetaplah tak bisa diganggu gugat. Dan ketika momen ketidakadilan seperti itu justru dipelopori oleh negara, maka, sebagaimana sejarah mencatat, insurgensi tinggal menunggu waktu.
Letupan-letupan kecil keresahan masyrakat Brasil mulai mendunia ketika kasus perbaikan stadion Maracana yang disinyalir menghabiskan dana hingga 600 juta dollar AS. Padahal, anggaran awal untuk penambahan fasilitas dan perbaikan mutu stadion diperkirakan “hanya” berkisar pada angka 350-400 juta dollar AS. Itu artinya, ada (dugaan) penyelewangan dana atau dengan kata lain: korupsi.
Contoh lain yang berhubungan dengan kasus mark-up dana termaktub dalam laporan tim auditor yang memeriksa proposal pembiayaan pembangunan Stadion Mane Garrincha . Dalam laporan itu disebutkan, dana yang terpakai untuk Stadion Mane Garrincha sebesar 900 juta dollar US—yang membuatnya menjadi stadion termahal kedua di dunia—ternyata telah hingga 3 kali lipat atau sekitar 275 juta dollar US.
Angka tersebut bahkan belum merupakan keseluruhan mengingat presentase pengerjaan proyek yang baru diaudit masih berkisar 25 %. Diduga kuat gelembungan dana tersebut masuk ke kantong para politis korup atau kepada pengusaha pemenang tender yang dekat dengan rezim pemerintahan Dilma Rousseff.
Pasca mengetahui beragam kabar tersebut, masyarakat Brasil yang sebelumnya telah menuntut pemerataan sekaligus stabilitas finansial, pemenuhan fasilitas publik seperti sekolah dan transportasi yang memadai, mulai menunjukan solidaritasnya. Dengan diinisiasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, mereka kemudian melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk kali pertama pada laga pembuka Piala Konfederasi antara tuan rumah melawan Jepang.
Pemerintah Brasil sendiri seolah mempersetankan aksi demonstrasi tersebut. Satu-satunya hal yang mereka lakukan sejauh ini demi meredakan suasana adalah dengan meminta Pele, salah satu pendekar sepak bola negeri Samba yang mengklaim dirinya telah mencetak 1000 gol lebih sepanjang karinya itu, berbicara di televisi. Dalam sebuah wawancara kepada O Globo TV, Pele berseru:
“Mari kita lupakan segala kerumitan ini, semua protes ini, dan mari mengingat bahwa tim nasional Brasil adalah kebanggaan negara dan darah kita.”
Meredakah situasi setelah Pele berkata demikian? Tentu saja tidak. Yang terjadi kemudian Pele justru menjadi sasaran caci maki oleh masyarakat Brasil, mulai dari jalan raya hingga dunia maya.
“Silakan pergi ke rumah sakit, naiklah bus yang tidak ada keamanannya, dan kita lihat apakah dia (Pele) masih akan berkata hal yang sama!” tulis salah seorang pemrotes di salah satu laman Facebook-nya.
Merasa disepelekan, demonstrasi pun digelar masyarakat dengan lebih intens dan mulai melibatkan nyaris seluruh para pekerja di sektor umum seperti guru, dokter, bahkan polisi dan tentara. Baru-baru ini, tepatnya pada 3 Juni 2014 kemarin, sekitar 5000 supir bus melakukan aksi massa di Sao Paolo yang menyebabkan kota tersebut dilanda stagnasi yang cukup parah. Masih di Sao Paolo, 50 orang polisi juga menggelar mogok kerja. Anehnya, aksi tersebut justru mendapat dukungan dari ribuan polisi di berbagai kota di Brasil.
Jika menengok ke penyelenggaran Piala Dunia sejak tahun 1998 silam, aksi massa yang dilakukan para pekerja seperti ini bukanlah hal asing. Di Prancis, misalnya, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 1998, para pekerja proyek pembangunan infrastruktur juga melakukan pemogokan massal lantaran minimnya jaminan keselamatan. Aksi serupa juga ditemui saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan empat tahun lalu.
Akan tetapi, berbeda dengan yang terjadi di Prancis maupun Afsel, aksi massa di Brasil—sebagaimana telah disinggung sedikit di atas—dilakukan oleh nyaris seluruh elemen pekerja yang menempati sektor penting. Tentu saja akan menjadi kendala yang amat besar bagi Brasil untuk melangsungkan Piala Dunia yang kondusif jika moda transportasi, sarana keamanan, hingga fasilitas kesehatan tidak memadai.
Aksi para pekerja tersebut secara tidak langsung mengakibatkan efek bola salju yang buruk kepada sektor lain. Dari segi keamanan, misalnya, aksi mogok 50 orang polisi—yang rencananya juga akan diikuti oleh ribuan polisi lain di seantero Brasil—membuat situasi keamanan menjadi tak terkendali. Itu artinya, kriminalitas akan merajalela di jalan-jalan, di tiap sudut gang, mengancam keselamatan para turis yang datang.
Sebagaimana dikutip dari laman Pandit Football Indonesia , angka kriminalitas di Brasil sendiri pada tahun lalu sejatinya sudah termasuk yang tertinggi di dunia dengan rasio 28 kasus per 100 ribu penduduk. Ahli keamanan Brasil, Paulo Storani, yang telah berkarir di kepolisian di Rio De Janiero selama 30 tahun mengatakan Associtated Press bahwa aksi kriminal telah meningkat hingga 50% pada 12 kota yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Storani berasumsi, selain beberapa kesatuan polisi yang ikut turun demonstrasi, resistensi para pengunjuk rasa yang tak kunjung henti ditengarai menjadi penyebab melonjaknya angka kriminalitas.
“Terfokusnya polisi mengamankan Piala Dunia dan mengatasi demonstran membuat banyak penjahat merasa lebih nyaman melakukan tindak kriminal, mereka merasa tidak akan ditangkap atau dihukum, sikap pemerintah yang meminta bantuan militer adalah bukti frustasi yang tertuang,” ucapnya kepada Associated Press, yang dikutip oleh Pandit Football Indonesia.
Melihat kenyataan ini, Amerika Serikat, negeri yang memang mengidap paranoid terhadap keamanan, bahkan sampai perlu membuat situs resmi “travel warning” yang ditujukan khusus kepada para warganya yang plesiran ke negeri samba tersebut.
Tak berbeda jauh dengan sekutunya, pihak Departemen Luar Negeri Inggris pun memberikan himbauan serupa kepada para penduduknya hingga agar berhati-hati saat hendak membawa uang di ATM, atau pada saat mengeluarkan telepon selular. Salah seorang wartawan Jawa Pos, Agung Putu Iskandar, termasuk salah satu korban penodongan ini. Agung harus merelakan telepon selularnya berpindah tangan dengan paksa.
Belum selesai persoalan kriminalitas di jalan-jalan Brasil, ancaman stabilitas keamanan kembali menyeruak setelah Badan Intelejen Brasil mengeluarkan enam laporan yang berpotensi mengganggu situasi terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Dalam laporan yang dilansir Guardian tersebut, salah satu ancaman datang dari organisasi kriminal Primeiro Comando da Capital (PCC).
Sekadar pemberitahuan, PCC memiliki anggota lebih dari 13.000 orang Organisasi ini berbasis di kota Sao Paolo namun memiliki banyak anggota di setiap kota-kota besar lainnya. Sebagaimana gangster kebanyakan, aktivitas PCC meliputi perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, serta sindikat penjualan narkoba.
Yang membuat PCC menjadi ancaman di Brasil sekarang adalah sikap “ideologis” mereka yang begitu membenci polisi. Dikutip dari Pandit Football Indonesia, pada tahun 2012 lalu tercatat 100 korban tewas dibunuh organisasi ini dan mayoritas adalah polisi.
Dari 13.000 anggotanya, sekitar 6000 anggota PCC lain saat ini tengah mendekam dalam penjara. Dengan situasi keamanan yang tidak menentu seperti sekarang di Brasil, asumsi yang mengatakan bahwa PCC akan menimbulkan kekacauan amatlah masuk akal. Terlebih, mengingat kepolisian Brasil sendiri masih “terpecah” antara yang pro demonstrasi dengan yang tidak. Kekhawatiran terbesar adalah PCC akan membuat kerusuhan di penjara dan tak tertutup kemungkinan mereka akan memaksa kabur.
Dengan segala kekisruhan massal yang terjadi, pemerintah Brasil, hingga saat ini, ironisnya masih juga belum menanggulangi permasalah tersebut dengan respon yang positif. Seolah tak mau rugi secara finansial atau sekadar menjaga citra di mata dunia, mereka justru “membalas” aksi rakyatnya tersebut dengan sikap keparat yang sungguh sangat tidak manusiawi.
Semua bermula dari surat Mikkel Johnson, salah seorang jurnalis independen Denmark, yang menyebut bahwa pemerintah Brasil telah membunuh banyak anak jalanan demi kepentingan pencitraan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Surat Johnson dalam bahasa Portugis bisa dilihat di sini.
Cerita Johnson bermula pada September 2013 lalu. Ketika itu ia sekadar hendak plesiran sejenak sembari mencari tiket salah satu pertandingan di Piala Dunia di kota Fortaleza. Akan tetapi, bukannya keasyikan yang ia rasakan selama perjalanannya, Johnson justru menemukan sebuah fakta yang membuatnya begitu jijik dan memilih untuk kembali ke negara asal.
Berikut isi surat Mikkel Johnson yang tertuang dalam surat kabar daerah – Tribuna de Ceará (15/4) lalu, seperti yang sudah dialihbahasakan oleh tim Pandit Football Indonesia:
“Piala Dunia tahun ini adalah sebuah ilusi besar yang disiapkan untuk orang asing. Hampir 2 setengah tahun yang lalu saya bermimpi meliput Piala Dunia sebagai event olahraga terbaik di dunia yang kebetulan di gelar di Brazil – sebuah negeri yang indah . Saya membuat rencana untuk pergi dan belajar bahasa Portugis disana.
Mimpi itu menjadi nyata, saya berangkat pada bulan September 2013. Tapi hari ini, 2 bulan sebelum pesta Piala Dunia digelar, saya memutuskan bahwa saya tidak ingin ikut ambil bagian dalam Piala Dunia. Mimpi indah saya di awal kini telah berubah menjadi mimpi buruk .
Selama 5 bulan tinggal di Brazil saya mendokumentasikan banyak hal konsekuensi buruk dari kehadiran Piala Dunia: penggusuran secara paksa, keberadaan angkatan bersenjata dan polisi militer di tengah masyarakat, korupsi, proyek-proyek sosial yang tertutup dan masih banyak lagi. Semua proyek dan perubahan yang mereka lakukan hanya untuk orang-orang seperti saya – orang asing – dan pers internasional . Yang mereka lakukan hanya untuk mencitra pada dunia luar.
Pada bulan Maret, saya berada di Fortaleza untuk mencari tahu kekerasan apa yang saat sering terjadi di kota-kota yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saya berbicara dengan beberapa orang dan mereka menyarankan saya untuk berinteraksi dengan beberapa anak jalanan, dan saya mendapati bahwa beberapa dari anak-anak ini telah menghilang.
Sering kali, mereka diculik dan dibunuh ketika mereka tidur di daerah yang banyak wisatawan berkunjung kesana. Mengapa hal itu dilakukan ? Tentu saja dalam rangka untuk membuat kota terlihat bersih bagi orang asing dan pers internasional? Dan bagi saya juga?
Di Fortaleza saya bertemu dengan Allison , 13 tahun , dia hidup di jalanan dengan kehidupan yang sangat sulit. Dia tidak punya apa-apa – hanya sebungkus kacang. Ketika kami bertemu, dia menawarkan saya semua yang dia punya (red; kacang).
Dengan kebaikan hatinya, bocah yang tidak memiliki apa-apa itu menawarkan kacang -sebuah barang berharga yang dia punya kepada saya – sosok orang asing yang membawa peralatan kamera senilai $4000 dan Master Card di dompet. Sesuatu yang mengharukan.
Hidup bocah tersebut terancam gara-gara orang asing seperti saya. Tak menutup kemungkinan dia akan menjadi korban pembersihan berikutnya di kota Fortaleza. Saya tidak bisa terus tinggal disini. Piala Dunia tahun ini tak saja sebagai Piala Dunia termahal dalam sejarah dalam konteks uang, tapi juga piala dunia yang mengorbankan kehidupan anak-anak muda.
Hari ini saya memutuskan untuk kembali ke Denmark. Kehadiran saya disini hanya akan membuat Brazil seolah menyenangkan dan baik-baik saja. Dua setengah tahun yang lalu saya bermimpi menjadi bagian dalam gelaran Piala Dunia, tapi hari ini saya akan melakukan segalanya, dengan kekuatan saya sebagai wartawan saya akan terus mengkritik dan fokus pada harga riil Piala Dunia yang kelewat batas.
Apakah anda ingin dua tiket untuk pertandingan Perancis melawan Ekuador, 25 Juni nanti?
Mikkel Johnson – Independent Journalist Denmark”
Dengan sederet fakta mengerikan di atas mengenai Piala Dunia 2014, ada baiknya kita bertanya ulang: seperti inikah pesta akbar sebuah turnamen olah raga yang dianggap sebagai penyatu keberagaman manusia yang semestinya kita tonton? Betulkah ini yang kita harapkan dari sepak bola?
Jawabannya jelas: tidak!
Bill Shankly, pelatih legendaris Liverpool, pernah melontarkan pernyataan bahwa sepak bola sesungguhnya lebih sakral dari hidup dan mati. Beruntung, Bill sudah wafat sejak 33 tahun yang lalu karena serangan jantung. Jika saja ia masih hidup dan pergi ke Brasil hari ini, mungkin Bill akan memanjat Cristo Redentor untuk kemudian terjun bebas ke bawah.
* * *
Naskah ini juga tayang di majalah Geo-Times edisi 15 yang terbit bulan Juni 2014