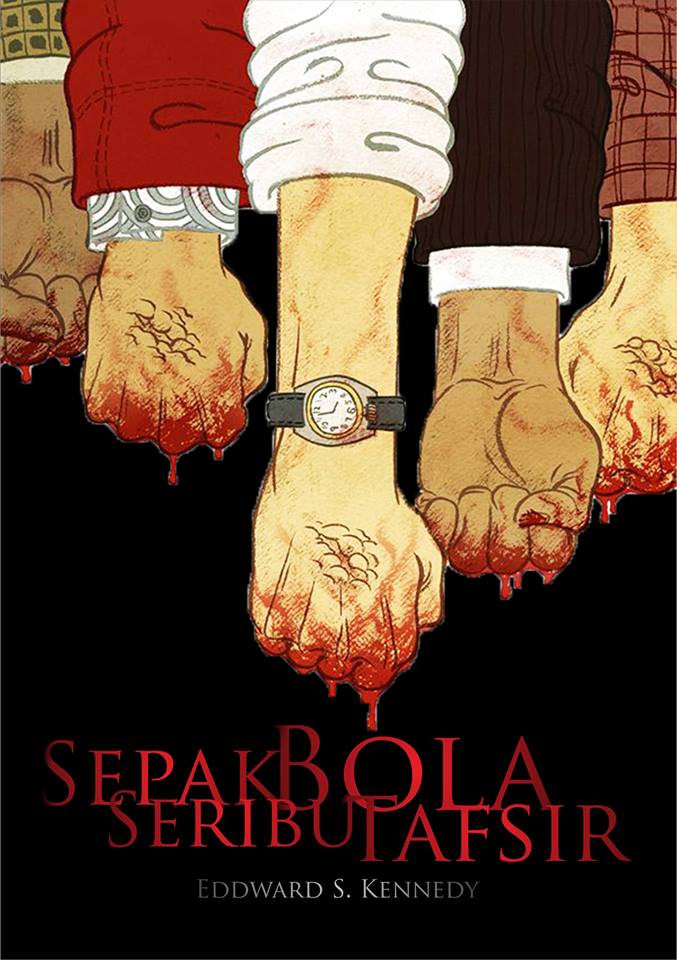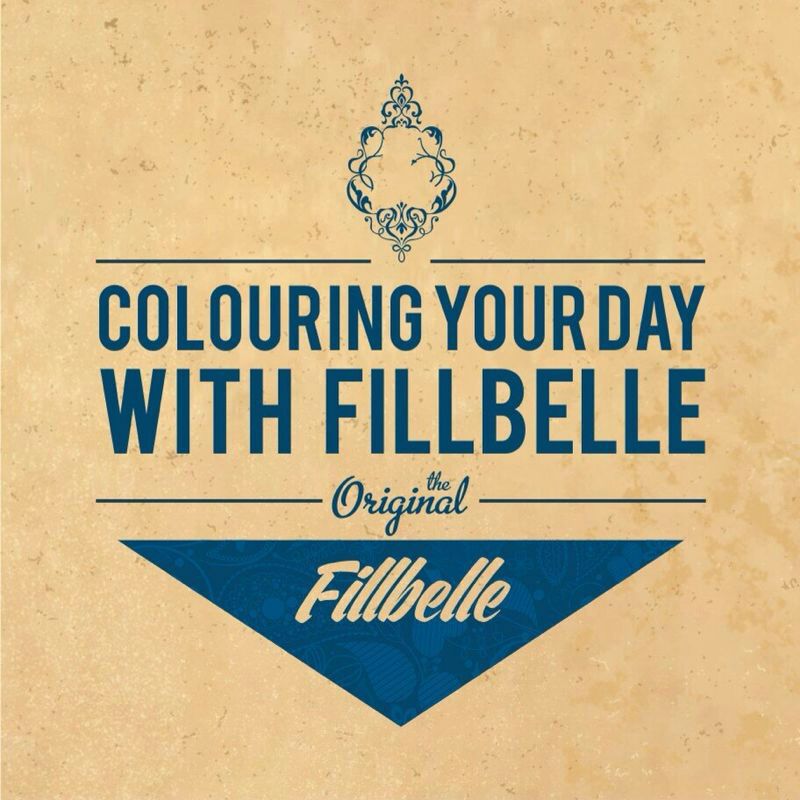Interaksi
Fotografi: Perbincangan Mooi Indie dan Gaya Hidup
Barthes pernah mengilustrasikan perihal lensa (kacamata) sebagai sesuatu yang dimitoskan. Kacamata merupakan alat bantu penglihatan bagi mereka yang mengalami cacat penglihatan. Manakala kacamata diterima sebagai sesuatu yang hanya menandakan kejeniusan, saat itulah kacamata telah dimitoskan, dan manakala lensa kamera beserta citraannya “hanya” menandakan keindahannya maka saat itu juga keindahan juga telah dimitoskan.
Saya sengaja memberikan ilustrasi tersebut sebagai pengantar untuk memasuki perbincangan lebih lanjut. Fotografi dan gaya hidup tengah menyiratkan semangat keindahan yang mendayu. Dengan kata lain, “semangat mooi indie” dan “mimpi generasi sebelumnya” (1960an) terbangun di dalamnya.
Onghokham dalam “Hindia yang Dibekukan: “Mooi Indie dalam Seni Rupa dan Ilmu Sosial” (1994) mengatakan bahwasanya barat secara intelektual telah menciptakan timur dengan begitu romantik. Ia secara sederhana mengungkapkan bahwa mooi indie adalah penggambaran alam dan masyarakat Hindia-Belanda secara damai, tenang, dan harmonis. Mooi Indie jelas ciptaan kolonial, meskipun warisanya hidup sampai hari ini. Jika nasionalisme Indonesia bersifat romantik, itulah bukti bahwa Mooi Indie telah pula mewarnainya.
Pengagungan citra landscape yang berlebihan tentu saja mengundang kegamangan yang lain. Jangan-jangan kita memang sedang teramat butuh penghiburan, atau jangan-jangan kita terlalu egois dan sedikit melupa pada realitas yang sebenarnya. Tentang pendidikan, kemiskinan, tentang kerusakan alam, atau tentang mereka yang terpinggirkan. Peduli amat. Pelesiran!, angkat kamera. Karena berfoto adalah kegembiraan masing-masing. Apakah senyatanya memang begitu?
Pelesiran atau lebih trendi dikatakan dengan istilah traveling telah menjadi sebuah gaya hidup yang kian mengukuhkan tren foto-foto landscape. Keterpesonaan citra visual menggiring mereka para traveler untuk menjamah, serta merayakan visualitas di mana mereka berkunjung. Melalui foto, mereka memilih, lalu mengeleminir bagian lain untuk ditiadakan, memasang pose yang “semringah”, lalu klik!, selfie! Dan unggah. “Berkunjung lalu berfoto maka aku ada”, mungkin adagium ini pas untuk disematkan.
Strassler dalam Refracted Visions: Popular Photography and National Modernity in Java (2010) dalam salah satu babnya menuturkan perihal fotografi populer dalam ruang studio foto dekade 1960an. Latar belakang (backdrop) dan aksesoris menjadi faktor penting dan tak terpisahkan. Bergaya dengan latar belakang yang dipilih seperti tengah menyiratkan mimpi dan cita-cita. Aksesoris yang digunakan seperti sepeda dan televisi menjadi perlambang modernitas, dan tentu saja menambah kegagahan. Mereka seperti tengah menyiratkan mimpi untuk merasakan seperti apa yang –akan- segera tampak dalam citra foto tersebut (setelah tercetak), melakukan perjalanan dan berfoto dengan latar belakang pemandangan yang mempesona.
Industri memang terus bergerak, meninggalkan yang lampau menuju pembaruan. Kita layak berterima kasih kepada teknologi. Berkat kehadiran kamera digital, kita tidak perlu lagi menggantungkan mimpi melalui backdrop studio foto. Kegembiraan akan “mimpi yang terwujud” terlahir melalui euforia para traveler merayakan modernitasnya.
Para fotografer, baik amatir ataupun profesional seperti tengah merayakan masanya. Mengunjungi tempat yang menarik lalu membingkainya dalam sebuah foto dengan polesan gaya salon. Kita tentu saja paham bagaimana gaya salon menjadi prestise tersendiri, menjadi parameter kegagahan pemotretnya. Perayaan inilah yang kemudian “menjebak” para travel fotografer pada gemerlap visualitas yang serba indah.
Dalam beberapa kesempatan kita mungkin sering mendengar: “Damn! Beautiful Indonesia”, “Wonderfull Indonesia atau “gillaaa keren banget!, aku cinta Indonesia! Jika yang demikian adalah sebuah perwujudan nasionalisme yang bersifat romantik, maka dapat dikatakan bahwa Mooi Indie telah turut mewarnainya, seperti apa yang dinyatakan oleh Onghokham dalam kutipan di atas.
Dalam ruang lingkup seni rupa modern Indonesia, Sudjojono pernah melancarkan kritikan keras perihal tampilan khas mooi indie. Ia menganggap mooi indie abai terhadap realitas yang sebenarnya, dan tak lebih hanya kemolekan yang diperuntukan untuk “menghibur orang-orang asing”.
Mooi Indie “hanya tertarik” pada keindahan alam yang harmonis dan “tidak pernah tertarik” pada keadaan sesungguhnya, seperti penderitaan para petani ataupun getirnya kehidupan orang-orang desa. Kita tidak pernah mengerti sedalam apa perasaan para petani, pencari rumput, atau mereka yang memiliki rumah di area pegunungan dan mereka yang terpinggirkan. Dengan kondisi yang serba terbatas, jauh dari hiruk pikuk modernitas. Dan kita berkecenderungan untuk berpendapat “aiih, enak sekali tinggal di sana, udaranya sejuk segar, pemandangannya indah!”. Enak bagi para traveler barang sehari dua hari, tentu saja.
Tentu saja, bagi mereka yang jarang atau tak pernah menyaksikan birunya lautan, hijau dan tenangnya hamparan persawahan dan sejuknya udara pegunungan akan mengatakan demikian. Semacam pelepas penat bagi mereka. Itulah pelancong, -maaf- lebih trendi dengan sebutan traveler. Kehadiran fotografi digital melahirkan tradisi yang bukan sekadar bertraveling ria, namun hasrat visual untuk memotretpun turut mengiringi.
“Benarkah foto-foto salon bukan suatu penandaan yang gamblang tentang gaya foto yang mewabah di Indonesia?” Pertanyaan ini saya ambil dari salah satu sub bab “salon” buku Photagogos: Gelap Terang Fotografi Indonesia (2013).
Pertanyaan tersebut mungkin hanya akan terasa sederhana dan selintas lalu, akan tetapi perlu sebuah perenungan untuk benar-benar memahaminya. Merujuk pada pertanyaan di atas, persoalan gaya hidup dapat dikatakan sebagai ujung pangkalnya. Gaya hidup diistilahkan sebagai cita rasa seseorang dalam hal fashion, aktivitas, maupun berekreasi. Dalam kerangka ini, gaya hidup “mengada” melalui travel fotografi –landscape- menjadi sebuah cara untuk memperlihatkan identitas, sekaligus pelepasan hasrat untuk berbeda, lebih gagah.
Para pelancong, maaf maksud saya: traveler, memotret bukan sekadar untuk mendapatkan foto yang menarik, tapi juga untuk mendapatkan status citra. Dalam ruang visual bernama fotografi, gaya hidup berkeinginan mengada tentu saja melahirkan kontestasi untuk “beradu” alat (kamera) dan juga citraan yang dihasilkan. Pemenuhan hasrat visual sebagai gaya hidup yang mewujud dalam traveling yang saya tuturkan di atas setidaknya bisa sedikit menerangkan bagaimana foto salon begitu mewabah dan menjadi gaya foto yang populer, yang gemari dan menjadi trend setter saat ini.
Agaknya kita perlu mengingat kembali atas apa yang pernah dikatakan oleh W. J. T. Mitchell perihal foto landscape, dalam Landscape and Power (2002) Ia pernah mengatakan bahwa Landscape bukanlah sebuah genre seni tapi –hanyalah- medium. Medium dalam menyampaikan pesan, bahwasanya foto landscape tidak hanya mengandung keindahan, namun ia menjadi media antara alam dan manusia serta budaya. Maka, sudah seharusnya kita bisa mengambil pesan dari apa yang ditampilkan foto landscape, bukan cuma sekadar mengambil keindahan demi terpuaskannya hasrat visual dalam diri.
Dan kita harus tetap mengingat bahwa di balik indahnya pegunungan, di balik birunya lautan, serta di balik hijaunya persawahan masih ada mereka yang terpinggirkan. Dan, Indonesia tak seindah foto landscape.
Daru Aji
Pemerhati fotografi