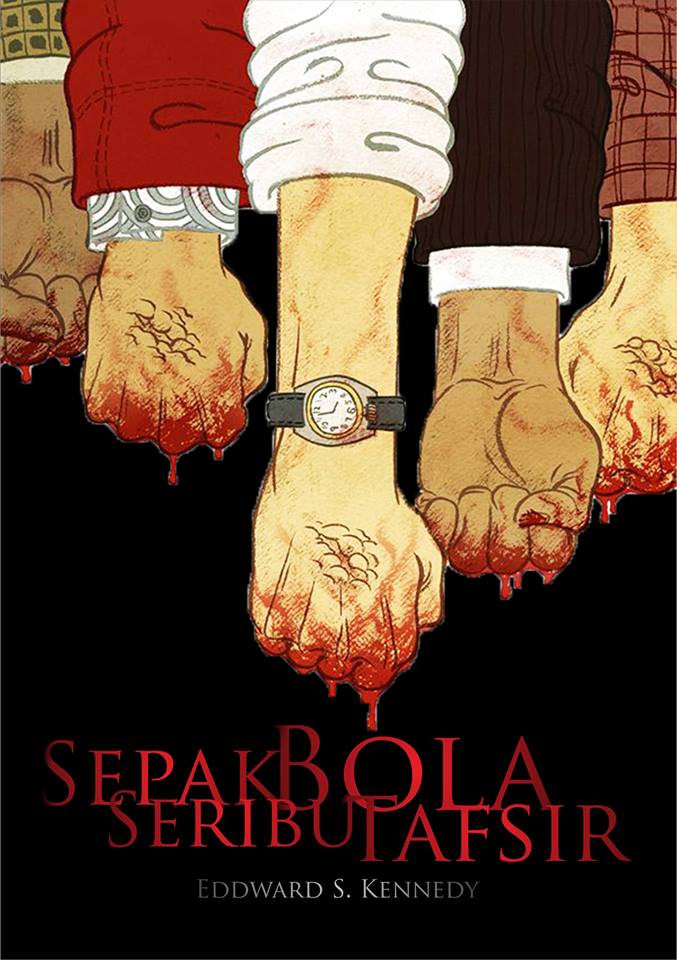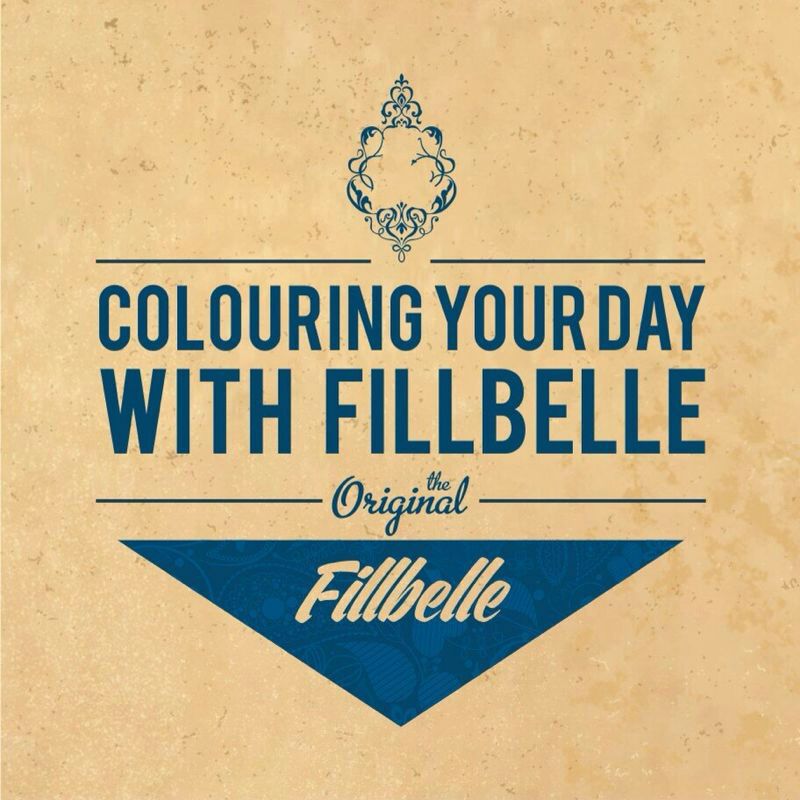Interaksi
Opini: Lebaran Politik dan Perayaan Visual Bernama Selfie
Setelah menunggu hampir dua bulan, akhirnya lebaran politik datang juga. Mungkin kita akan mengingat 9 Juli sebagai tanggal yang cukup emosional. Sosial media yang pada awalnya adalah ruang interaksi virtual yang menyenangkan berubah menjadi ruang kampanye. Ruang dimana wacana antar capres saling dibenturkan, saling beradu. Ada yang benar, merasa benar, bahkan ada yang merasa harus dibenarkan.
Kita bisa membayangkan bagaimana ruang pribadi yang terkoneksi dengan publik serta merta berubah menjadi ruang kampanye tanpa henti. Ruang virtual (baca: sosial media) tak ubahnya seperti perpanjangan tangan industri media. Dalam hal ini, pengguna sosial media adalah bagian dari masyarakat siber yang terus melakukan pemaknaan melalui akun pribadinya dengan prospektus pemilu yang terwujud dalam bentuk status, twit, maupun foto.
Ruang virtual memungkinkan siapapun untuk menjadi apa yang diinginkan. Melalui status, komentar, twit ataupun foto, seseorang bisa mengkonstruksikan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang diinginkan. Atas sifatnya yang cair, pembicaraan dalam ruang virtual selalu mengikuti wadah (lingkungan) nyatanya. Seperti yang kita saksikan kali ini, suasana pilpres merasuk dalam ruang virtual lengkap dengan bumbu data, opini, atau bahkan terkadang status berbau fitnah yang mewujud dalam postingan seseorang.
Kita mengingat bagimana neuromancer (1984) telah mengenalkan perihal cyberspace kepada pembaca. Gibson (penulis nover tersebut) memetakan teknologi baru yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam menciptkan individu-individu dan lingkungan baru. Kita bisa sama-sama menyaksikan, bagaimana sosial media memberikan pengaruh kesenangan bahkan kejengahan yang luar biasa dalam hajatan pilpres kali ini.
Seiring berkembangnya cyberspace, ia menjadi podium yang hangat bagi menetasnya ruang baru bernama cyberculture. Cyberculture memberikan tawaran baru perihal “kesadara pasca-ruang”, dimana seluruh aktifitas dilakukan dalam ruang virtual. Bukan hanya menghubungkan relasi manusia sebagai penggguna dan mesin (jaringan computer)saja namun cyberculture juga melihat bagaimana hubungan kepribadian manusia dengan teknologi Salah satu yang mewujud dari hubungan kepribadian dan teknologi adalah memotret diri sendiri, atau lebih popular kita sebut sebagai selfie.
Foto selfie bukan sekadar aktualisasi diri dalam rangka melakukan interaksi, namun ia menjadi sebentuk tontonan. Penonton sebagai konsumen akan memilih caranya sendiri dalam berkomentar dan memaknai. Foto selfie ini biasanya membawa pesan fashion maupun berupa politik diri sebagai proyek representasi. Gelaran coblosan banyak menetaskan foto selfie dengan ragam bentuk dan corak. Kita bisa telusuri akun-akun sosial media. Ada berapa banyak foto selfie yang bisa ditemui hari ini?jawabnya:banyak.
Mereka berdandan dan “meminjam” kode fashion salah satu pasangan capres, hal ini bukan sekadar kegembiraan lebaran politik, namun juga menunjukan keinginan dirinya untuk mengada sekaligus membentuk proyek representasi atas keberpihakan kepada salah satu calon. Bukan hanya melalui fashion, dengan menampilkan jari bercap tinta biru juga menjadi ke”aku”an yang melegitimasi dirinya sebagai pemilih. Ada yang satu jari, namun ada juga yang dua jari sekaligus. Hal tersebut menjadi penanda sikap sekaligus cermin sosial.
Sebagai wacana, kita tentu paham bagaimana teks (foto) digerakan oleh praktik-praktik kewacanaan yang menghubungkan antara produsen dan konsumen teks. Produsen (fotografer) bekerja dalam institusi dirinya sendiri. Mirip kondisi bercermin, ia memilih pose dengan tujuan yang ia inginkan. Tentunya apa yang ia inginkan berpijak pada peran sosikultural masyarakat siber. Mengada, menarik perhatian, mengajak untuk sama, dan membicarakan dirinya sendiri sebagai “aku”. Seusai pencoblosan kita tak akan menemui foto selfie dipajang di depan rumah, kecuali dipajang di rumah maya bernama sosial media.
Dengan berselfie kita memberikan penguasaan visual atas diri sendiri dan hal tersebut menjadi cara kerja kultural dalam penegasan berpolitik. Citraan visual (Selfie) mewakili orang-orang dalam kelompoknya, dengan demikian ia menunjukan sebuah versi dari tampilan diri, baik individu atau kelompok secara sosial maupun kelas.
Ketika ia berfungsi sebagai lahan mengada, tentunya selfie membuka celah persinggungan dengan gaya hidup. Selfie menjadi cara manusia modern dalam memberikan makna atas dirinya sendiri sekaligus menyiratkan relasi simbolik antar manusia yang membutuhkan aktualisasi dalam realitas virtual dan juga gaya hidup. Senyatanya, gaya hidup seseorang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi serta kemampuan seseorang dalam menyerap isu-isu di lingkungannya.
Ada kontestasi yang menarik ketika memilih (nyoblos) menjadi perayaan. Nyoblos adalah puncak dari kampanye politik. Dengan nyoblos, kita menentukan pilihan setelah beberapa waktu terombang-ambing dalam suasana kampanye. Sebagai pengguna sosial media, tentunya kita melihat bagaimana para pemilih merayakan hak nya dengan berfoto selfie. Dengan menjadikan diri sendiri sebagai model dan menguasakan lensa pada diri sendiri, artinya ia mencoba merekonstruksi tatanan fotografis tubuhnya sendiri. Namun, apa yang terlihat bukanlah sosok dirinya secara utuh dan natural, melainkan tatanan simbolik yang menjadi struktur visual untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Dengan mengatakan dirinya sebagai “aku” maka ia berusaha mencapai suatu kondisi yang diinginkan. Meski selanjutnya ke“aku”an ini akan dihadapkan pada “liyan”, yakni yang terlihat dalam foto. Selanjutnya, “liyan” inilah yang kemudian dikatakan sebagai “aku”.
“aku mengikuti tren (berselfie) maka aku ada”, kurang lebih adagium ini pas untuk disematkan.
Konsep subjektivitas dan identitas terkait erat dan secara virtual tak dapat dipisahkan. Sebagai perwujudan “subjektivitas” akan identitas dirinya, kita melihat kondisi menjadi seorang pribadi dan proses dimana kita menjadi seorang pribadi yang dibentuk sebagai subjek. Sebagai “subjek untuk” diri kita dan orang lain, inilah yang oleh Chris Barker dikatakan sebagai bentuk identitas diri.
Akhirnya, lebih dari sekadar kata narsistik ketika diri sebagai subjek memiliki kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai objek. Dan selfie adalah sebuah “kebanggaan” atas cerita tentang “aku”, maka kita tengah merayakan visualitas. Dalam konteks ini, Lebaran politik dan Perayaan visual itu bernama Selfie.
Daru Aji
Pengamat Fotografi